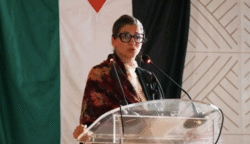Ambisi Keuchik dan Siasat Licik Pertahankan Tahta
INISIATIF.CO – Aceh, sebagai daerah istimewa, memiliki hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Salah satu ciri khas ini tercermin dalam Pasal 115 ayat (3) yang mengatur masa jabatan keuchik (kepala desa) selama 6 tahun.
Namun, belakangan ini, beberapa keuchik di Aceh mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menuntut masa jabatan 8 tahun, sama seperti yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 yang berlaku secara nasional.
Di satu sisi, tuntutan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan hukum. Namun, di sisi lain, hal ini justru mengancam keistimewaan Aceh yang selama ini diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Aceh memiliki otonomi khusus untuk mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk dalam hal masa jabatan keuchik. Jika MK mengabulkan permohonan ini, maka ciri khas tersebut akan hilang, dan Aceh akan semakin kehilangan identitasnya sebagai daerah istimewa.
Argumen yang mendukung masa jabatan 8 tahun adalah bahwa keuchik memiliki waktu lebih panjang untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa. Namun, apakah benar bahwa masa jabatan yang lebih lama akan menghasilkan kinerja yang lebih baik?
Teori kekuasaan menunjukkan bahwa semakin lama seseorang berkuasa, semakin besar potensi penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Lord Acton pernah mengatakan, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Artinya, kekuasaan yang terlalu lama dapat melahirkan korupsi, nepotisme, dan stagnasi dalam pemerintahan.
Sebaliknya, masa jabatan yang lebih singkat (6 tahun) sebenarnya dapat menjadi motivasi bagi keuchik untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Dengan waktu yang terbatas, mereka akan fokus pada perencanaan yang matang dan pelaksanaan program yang tepat sasaran.
Tidak dapat dipungkiri memang, tuntutan judicial review ini juga mencerminkan tren yang memprihatinkan, siasat merubah aturan demi kekuasaan. Di tingkat nasional, kita telah melihat bagaimana undang-undang dimanipulasi untuk memperpanjang masa jabatan atau memperluas kewenangan. Kini, praktik ini merambah hingga ke level gampong (desa). Jika MK mengabulkan permohonan ini, maka pesan yang tersampaikan adalah bahwa aturan dapat diubah demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Kepemimpinan nasional telah memberikan contoh buruk yang kini dipraktikkan oleh pemimpin di bawahannya. Ini adalah lingkaran setan yang harus dihentikan. Kekuasaan seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat, bukan untuk memperkaya diri atau memperpanjang jabatan.
Lantas, masa jabatan 6 tahun dengan 8 tahun, apakah benar-benar berbeda. Pada dasarnya, perbedaan masa jabatan 6 tahun dan 8 tahun tidak signifikan jika keuchik bekerja dengan perencanaan yang baik dan target yang jelas. Kunci keberhasilan bukan terletak pada lamanya masa jabatan, tetapi pada integritas, visi, dan kemampuan pemimpin dalam mengelola pemerintahan desa. Jika seorang keuchik memiliki komitmen yang kuat untuk membangun desa, maka 6 tahun sudah lebih dari cukup untuk menghasilkan perubahan yang berarti.
Jika dilihat dari sudut lain, judicial review yang diajukan oleh para keuchik di Aceh bukan hanya sekadar upaya untuk menciptakan kesetaraan hukum, tetapi juga mencerminkan nafsu kekuasaan yang semakin menggejala. Aceh, sebagai daerah istimewa, seharusnya mempertahankan ciri khasnya dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Masa jabatan 6 tahun bukanlah penghalang untuk mencapai kemajuan, asal dikelola dengan perencanaan yang matang dan integritas yang tinggi.
Alih-alih memperpanjang masa jabatan, para keuchik seharusnya fokus pada bagaimana memanfaatkan waktu yang ada untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Perubahan aturan demi kekuasaan hanya akan merusak tatanan demokrasi dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Saatnya kita menghentikan tren ini dan kembali pada esensi kekuasaan, yaitu melayani, bukan menguasai.[]